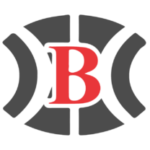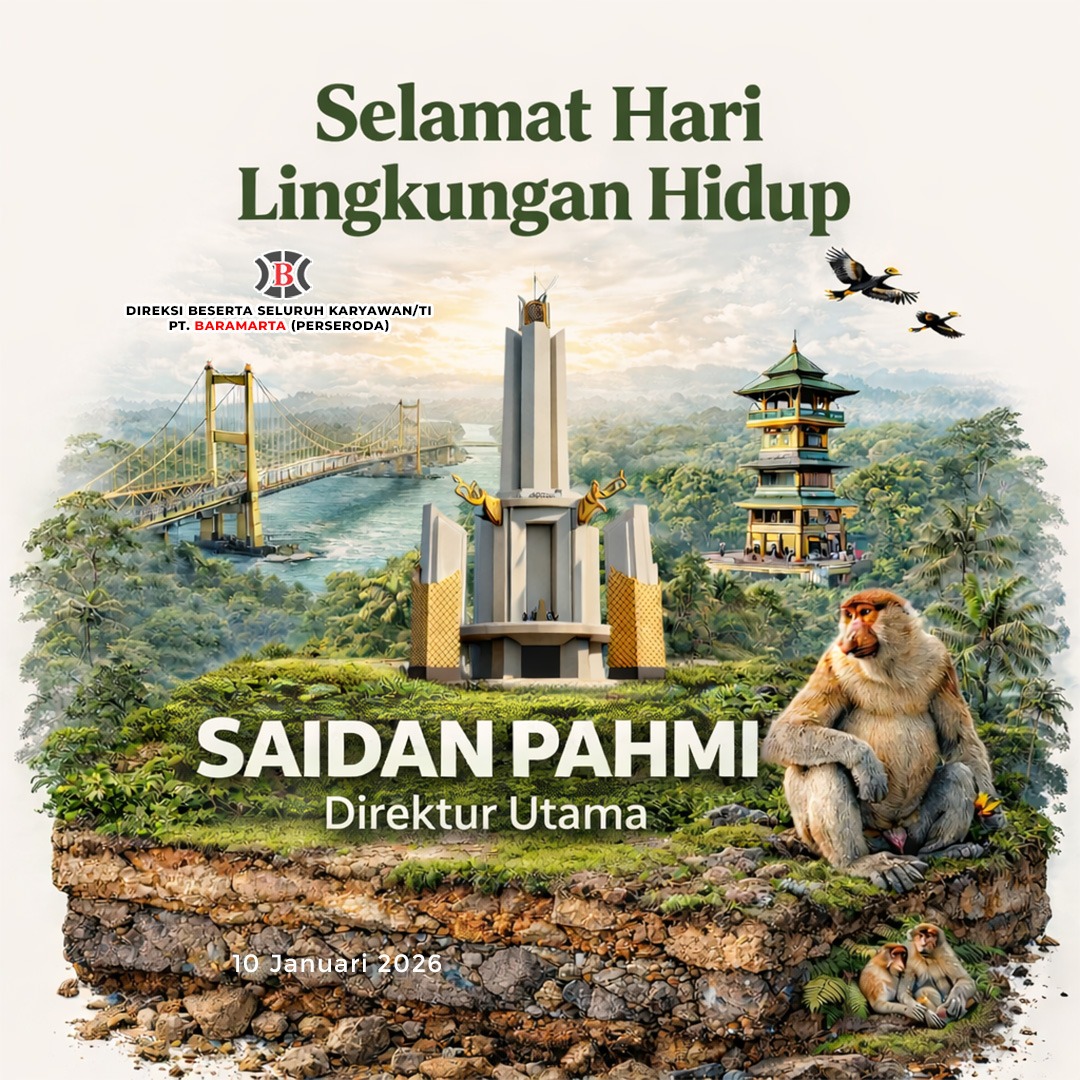Saat para pejabat sibuk memamerkan grafik pertumbuhan ekonomi di ruang ber-AC, sebagian ibu rumah tangga di kampung masih harus mencari kayu bakar karena gas melon 3 kilogram makin sulit dijangkau. Ironi ini menjadi potret nyata bahwa angka makroekonomi yang mengilap belum tentu sejalan dengan isi dapur rakyat kecil.
Indonesia sesungguhnya dikaruniai sumber energi melimpah: cadangan nikel terbesar di dunia, potensi panas bumi puluhan gigawatt, hingga tenaga surya dan air yang nyaris tak terbatas. Namun, sebagian besar kekayaan itu masih diekspor mentah tanpa nilai tambah berarti bagi rakyat.
Model pembangunan semacam ini menjual murah sumber daya dan membeli mahal teknologi telah berlangsung puluhan tahun. Akibatnya, kekayaan alam menguap keluar negeri, sementara rakyat di dalam negeri tetap harus membayar mahal harga energi dan kebutuhan pokok.
Korea Selatan menjadi contoh kebalikan. Negara tanpa nikel dan batubara itu justru berinvestasi besar dalam ilmu pengetahuan dan kualitas manusia. Kini, mereka menjadi pusat teknologi dunia. Sebaliknya, banyak negara kaya sumber daya termasuk di Amerika Latin dan Afrika justru terjebak dalam “kutukan sumber daya”: alam melimpah, tapi rakyatnya tetap miskin.
Indonesia kini berada di persimpangan sejarah. Apakah akan berani keluar dari kutukan itu, atau mengulang kegagalan yang sama?
Langkah awal untuk keluar sebenarnya sederhana: setiap izin tambang dan proyek energi wajib melalui audit sosial-ekologis agar eksploitasi tak merusak lingkungan dan merugikan masyarakat sekitar.
Selain itu, investasi asing harus tunduk pada prinsip martabat bangsa termasuk kewajiban transfer teknologi ke politeknik lokal, pembagian manfaat untuk desa, dan penghormatan terhadap adat dan ekologi.
Pemerintah juga perlu memacu riset energi lokal. Energi tidak harus selalu berasal dari proyek raksasa. Dari desa-desa bisa lahir inovasi seperti biogas, bio-LPG dari limbah pertanian, dapur induksi surya, hingga teknologi tambang berkeadilan asalkan negara mau memberi ruang dan dukungan nyata.
Aspek lain yang tak kalah penting adalah kedaulatan data energi nasional. Selama data distribusi LPG, listrik murah, dan migas masih disimpan di server asing, miliaran dolar devisa akan terus bocor keluar negeri. Norwegia dan India sudah melindungi datanya di sistem digital nasional, sementara Indonesia masih menyewa ruang di hyperscaler asing.
Rakyat sesungguhnya tidak menuntut kemewahan. Mereka hanya ingin energi yang terjangkau tanpa antre, harga pangan yang wajar, dan pekerjaan yang bermartabat.
Keadilan energi bukan berarti semua orang mendapat harga murah, tetapi memastikan yang paling rentan tidak ditinggalkan. Energi bukan sekadar listrik dan BBM ia adalah pertahanan, kedaulatan, dan kehormatan bangsa.
Indonesia terlalu besar untuk sekadar jadi penonton dalam transisi energi global. Sudah saatnya energi dilihat bukan sebagai komoditas dagang, melainkan sebagai pilar martabat nasional.
Sejarah tidak akan menunggu. Pilihannya hanya dua: berani mengubah arah, atau terus terjebak menjadi negeri kaya yang rakyatnya tetap miskin.